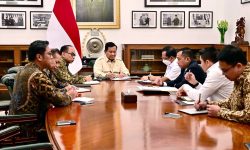Yang ketiga adalah, komitmen untuk sikap wara’, menjaga diri dari yang syubhat, atau ketidakjelasan. Wara’ dalam bahasa Arab berarti menjaga diri, khususnya dari perkara yang tidak jelas atau meragukan. Dalam konteks agama, wara’ adalah berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang haram atau yang syubhat (meragukan).
Orang yang memiliki sifat wara’ adalah orang yang menjaga diri dengan sangat hati-hati dalam setiap tindakannya, memastikan bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan syariat dan tidak mendekati hal yang dilarang oleh Allah.
Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, “Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka ia telah jatuh dalam yang haram.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadits ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih tindakan dan menghindari segala bentuk yang meragukan.
Dalam konteks konsumsi, jika ada ketidakjelasan mengenai status halal-haramnya, maka untuk kepentingan kehati-hatian, maka perlu dihindari hingga ada kejelasan halal-haramnya. Ketika kita menjadikan pusat kuliner menjadi salah satu destinasi untuk bersilaturrahmi, tempat bertemu dan menjamu sanak saudara, maka harus dipastikan pusat kuliner tersebut telah jelas kehalalannya.
Pada saat kita hendak memilih pusat jajanan atau restaurant untuk makan, sementara belum jelas halal-haramnya, belum ada tanda sertiikat halalnya, maka sudah seharusnya kita menghindarinya, sebagai upaya menjaga diri dari yang syubhat. Ini bagian dari sifat wara’ yang menjadi elemen penting dalam menjaga integritas diri, agar tidak terjerumus kepada yang dilarang.
Demikian juga dalam konteks tindakan, khususnya dalam hal penghukuman. Jika ada keraguan dalam memperoleh bukti apakah seseorang bersalah atau tidak, maka langkah yang hati-hati adalah mengambil jalan untuk memaafkan dan tidak menghukum. Tidak boleh memaksakan diri menghukum seseorang tanpa bukti yang meyakinkan.
Ada kaedah hukum Islam yang dapat dijadikan panduan, yaitu: Hukum gugur karena sesuatu yang syubhat.Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, “Hindarilah hukuman-hukuman sebab adanya sesuatu yang syubhat (ketidakjelasan) dari orang-orang Islam semampumu. Apabila engkau menemui jalan keluar (selain hukuman), maka tempuhlan jalan itu.”
Jika ada keraguan dalam pengumpulan bukti mengenai dugaan kesalahan, maka kita dilarang memaksakan diri untuk menghukum seseorang, hingga ada bukti-bukti valid yang menunjukkan kesalahannya. Bahkan, ketika ada kesalahan, sementara orang yang bersalah tersebut mengakui dan ada komitmen untuk melakukan perbaikan, maka sedapat mungkin mencari jalan keluar perbaikan tanpa harus dengan pendekatan penghukuman.
Karenanya, kesalahan dalam memberikan permaafan lebah baik dari pada kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, sebagaimana kaedah hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi SAW, “Salah dalam memaafkan lebih baik dari pada salah dalam menghukum.”
Dalam konteks relasi sosial, orang yang bersikap wara’ cenderung untuk lebih banyak diam dan mendengar, menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Orang yang wara’ akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, tidak menyebarkan kebohongan atau fitnah. Ia akan memastikan bahwa kata-katanya tidak mengarah kepada hal yang merusak atau menyesatkan orang lain.
Rasulullah SAW mengingatkan kita, “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dengannya, maka Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut.” (HR. Bukhari).
Dalam pelayanan sosial, orang yang bersikap wara’ cenderung memberikan kemudahan dalam urusan orang lain, serta menutup aib orang lain dengan tidak mengumbarnya menjadi bahan gunjingan.
Ini sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya.” (HR. Muslim).
Sebagai catatan akhir, usai Ramadhan, akan ada sebelas bulan ke depan sebagai ujian lapangan atas kegagalan dan/atau keberhasilan Diklat Ramadhan yang telah kita tempuh dalam sebulan. Jangan sampai puasa kita tak memperoleh apa-apa, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga.
Sebagaimana disindir oleh baginda Rasulillah saw dalam hadisnya, “Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga.” (HR An-Nasai dan Ibnu Majah).
Puasa yang berkualitas merupakan puasa istimewa yang dapat dicapai bukan sekadar menggeser waktu makan dan minum, tetapi juga mengendalikan nafsu, mampu menjaga lisan, membiasakan kejujuran, dan sifat wara’ dalam kehidupan. Mari kita manfaatkan momentum pasca Ramadhan untuk terus membangun peribadi berintegritas.
Puasa yang telah kita jalani seharusnya menjadi bekal untuk hidup yang lebih baik, menjaga lisan, lebih jujur, amanah, wara’ dan penuh dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga integritas dan terus memperbaiki diri dalam setiap aspek kehidupan.*
Prof. Dr. KH M. Asrorun Niam Sholeh, MA, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa/Pengasuh Pesantren al-Nahdlah Depok.